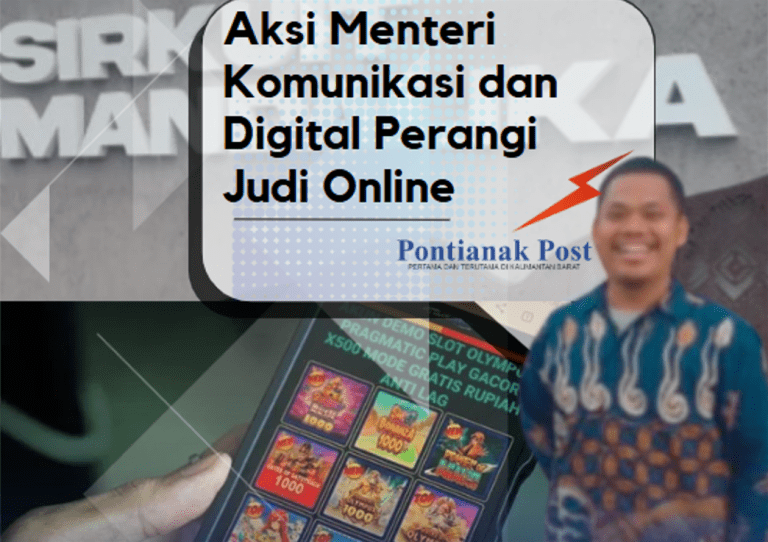Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan Universitas OSO Laksanakan Survei Lapangan di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang

Jagoi Babang, Bengkayang, 20–23 Juli 2025 Tim peneliti gabungan dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (UNTAN) dan Fakultas Hukum Universitas OSO (UNOSO) melanjutkan rangkaian kegiatan penelitian di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Kegiatan survei partisipasi dan persepsi masyarakat kali ini dilaksanakan di…